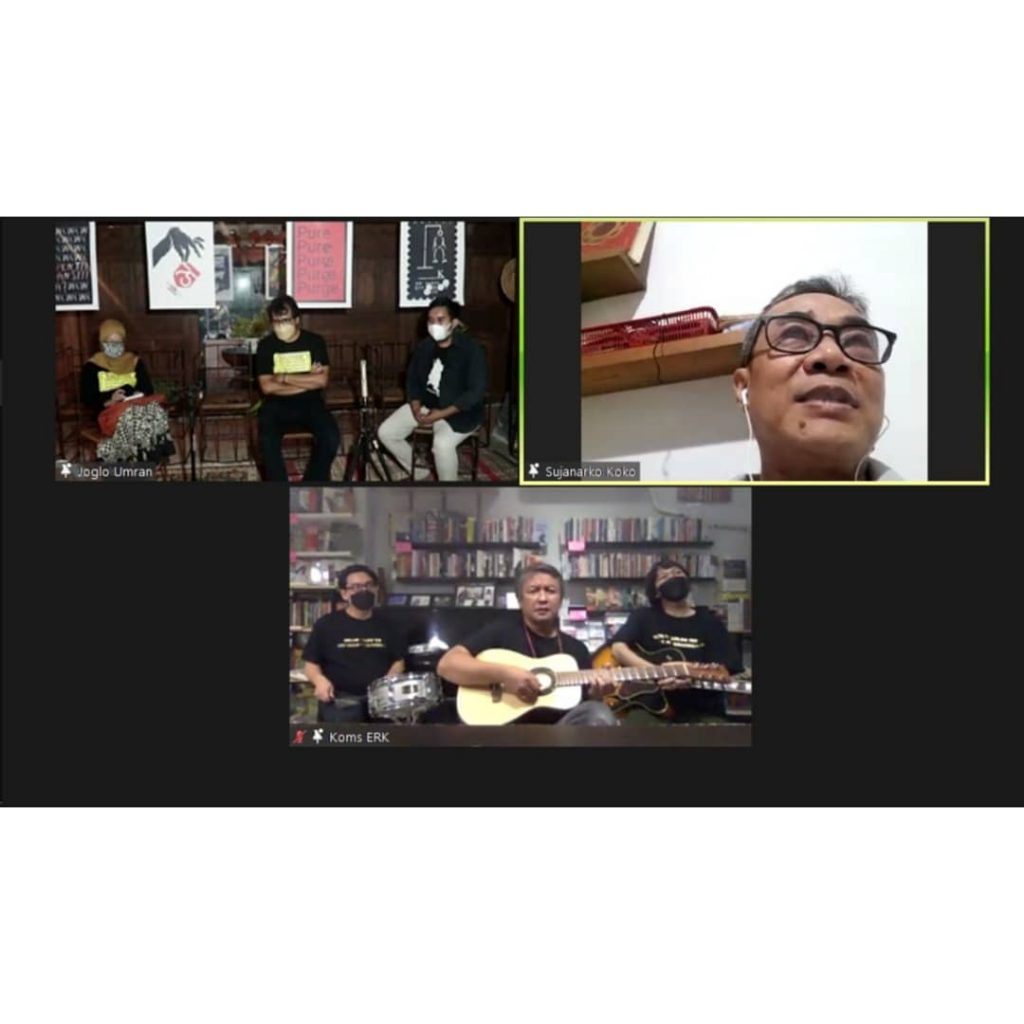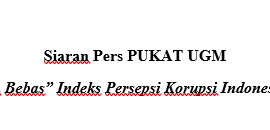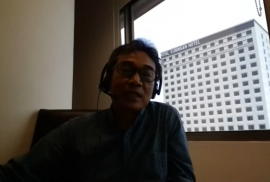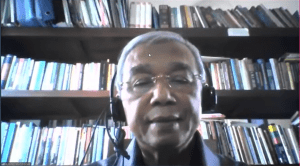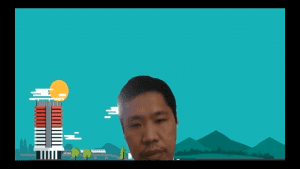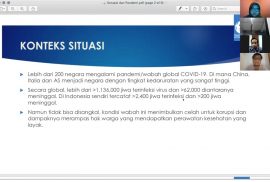Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menggelar diskusi publik DIKSI (Diskusi Seputar Korupsi) pada Rabu, 10 September 2025. Dengan tema “Menimbang Komitmen Agenda Reformasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Prabowo”, diskusi ini menghadirkan praktisi hukum sekaligus peneliti Centra Initiative, Erwin Natosmal Oemar, sebagai narasumber utama.
DIKSI kali ini dalam rangka menjawab kondisi Indonesia yang kini berada di sebuah persimpangan krusial. Agenda reformasi hukum dan pemberantasan korupsi yang menjadi amanat reformasi menghadapi tantangan berat di era pemerintahan baru. Berbagai persoalan lama, seperti jual beli perkara, penggunaan hukum sebagai alat politik, hingga sikap represif aparat, masih menjadi bayang-bayang yang mengancam tegaknya keadilan.
Dalam paparannya, Erwin Natosmal Oemar memberikan pandangan tajam mengenai kondisi penegakan hukum saat ini. Menurutnya, situasi yang dihadapi bukan lagi sekadar stagnasi, melainkan sebuah kemunduran.
“Situasi hari ini membuat kita sulit untuk berbicara tentang anti-korupsi. Ini bukan lagi persimpangan jalan, tapi sebuah penurunan,” tegas Erwin.
Ia menyoroti berbagai indeks reformasi hukum yang menunjukkan tren negatif. Hal ini menjadi sinyal bahaya bahwa upaya untuk membangun sistem hukum yang adil dan akuntabel sedang berjalan di tempat, bahkan mundur.
Erwin juga menekankan hubungan erat antara perlindungan hak-hak sipil dan keberhasilan agenda pemberantasan korupsi. Upaya memberantas korupsi tidak akan pernah optimal jika ruang gerak masyarakat sipil untuk bersuara dan mengawasi justru dibungkam.
“Berat rasanya memajukan agenda anti-korupsi kalau hak-hak sipil dan politik dibungkam. Keduanya saling berkaitan erat,” tambahnya.
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa demokrasi yang sehat dan kebebasan sipil merupakan fondasi esensial bagi terciptanya pemerintahan yang bersih.
Perlunya Pendekatan Teknokratis, Bukan Sekadar Tuntutan
Lebih dari sekadar melayangkan kritik, Erwin mendorong masyarakat sipil dan para akademisi untuk mengubah pendekatan. Menurutnya, untuk mendorong perbaikan yang nyata, desakan publik harus diimbangi dengan tawaran solusi yang bersifat teknis dan teknokratis.
“Norma hukum kita seringkali tidak jelas. Untuk memperbaikinya, perlu ilmu-ilmu teknis. Kita bukan hanya harus meminta, tetapi juga menyodorkan konsep teknokratis yang solid untuk perbaikan, mulai dari isu legalitas, hak asasi manusia, hingga akses terhadap keadilan,” jelasnya.
Diskusi menyimpulkan bahwa upaya mengembalikan hukum pada tujuan mulianya, seperti menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, membutuhkan sebuah gerakan kolektif. Diperlukan perubahan paradigma yang mendasar, tidak hanya di tingkat kelembagaan, tetapi juga pada sikap dan perilaku para penyelenggara negara. Tanpa komitmen tulus dan langkah sistematis, agenda reformasi hukum hanya akan menjadi jargon kosong.
Tentang PUKAT FH UGM
Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) adalah pusat studi di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang berfokus pada kegiatan penelitian, advokasi, dan edukasi publik untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi di Indonesia.